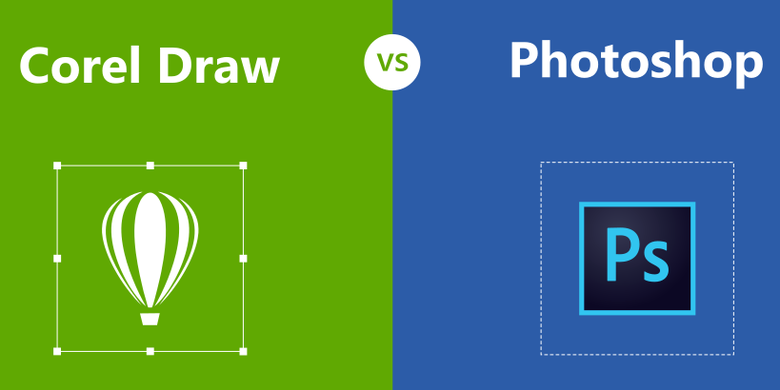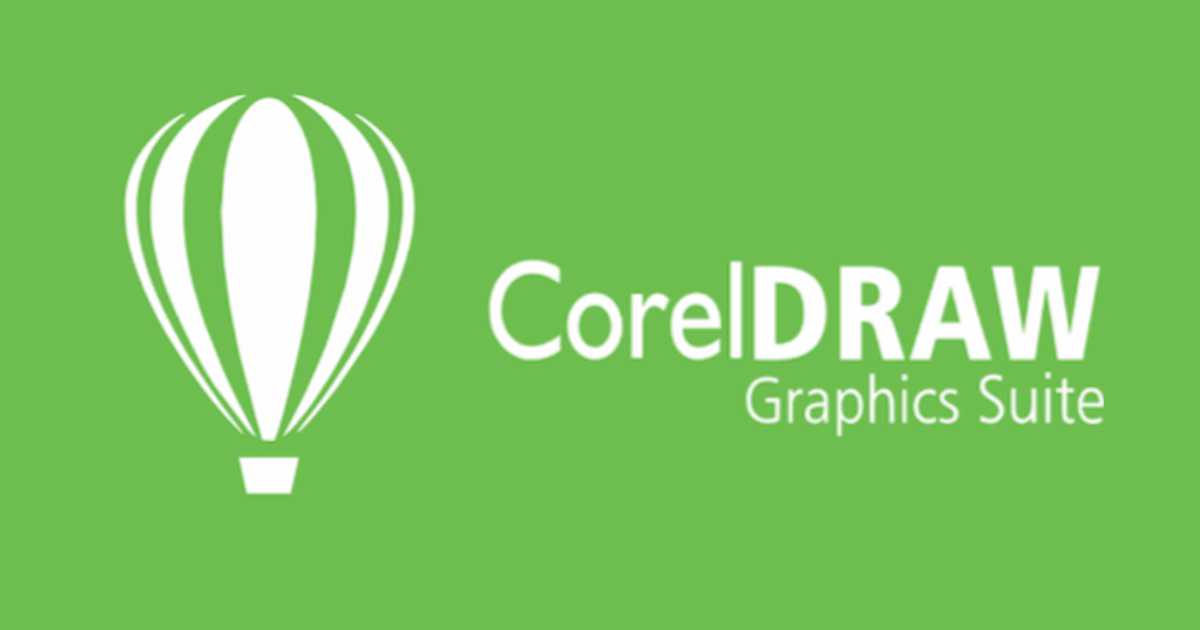Dalam forum tersebut, hadir para tokoh agama dan pimpinan pesantren yang sangat disegani. Diantaranya, KH MA Sahal Mahfudh dan fungsionaris PBNU Drs. H. Ahmad Bagjda. Sebagai pengundang sekaligus penyelenggara acara ini, yang juga para kiai khas; KH Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Dimyati Rois, KH Mahfud Ridwan MA, KH Dian Nafi’, dan KH A Muadz Thohir. (SM, 16/12).
Lontaran tersebut, sekilas terkesan biasa saja, namun jika kita cermati lebih dalam akan menarik rasanya.
Menarik?
Penulis menyebut lontaran Gus Mus—panggilan akrab Mustofa Bisri—menarik karena, pertama, kata-kata ini keluar dari seorang tokoh agama (sebut kiai) yang menjadi panutan dan sosok lebih dari kaum nahdliyyin (NU).
Nah, jika beliau adalah seorang tokoh NU, pertanyaan yang muncul kenapa tidak kemudian menampilkan (ketertarikan pada) organisasi kepemudaan yang menjadi ‘anak kandung’ dan masih sedarah dengan NU, seperti IPNU-IPPNU (ikatan pelajar nahdlatul ulama) dan PMII (pergerakan mahasiswa islam Indonesia) di tingkat universitas atau kampus?
Kedua, secara ideologis, jelas antara HMI (himpunan mahasiswa islam) dan Gus Mus sendiri sebagai pribadi maupun kelembagaan NU, tidak ada hubungan yang cukup signifikan, sehingga menjadi penyebab munculnya lontaran tersebut.
Inilah yang akhirnya menjadi pembuka bagi ketertarikan penulis untuk membahas lontaran Gus Mus ini menjadi lebih menarik dan penuh makna.
Asumsi yang bisa dimunculkan kemudian; apakah Gus Mus tengah melontarkan pujian dan nilai yang plus untuk organisasi HMI, atau justru tengah melakukan kritik terhadap NU sendiri beserta PMII dan varian organisasi di bawahnya. Itupun lebih disebabkan oleh gerakan-gerakan politiknya yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik?
Penulis mulai dengan memposisikan Gus Mus pada aras dan kutub organisasi NU beserta keluarga besar organisasinya, di satu sisi. Sementara HMI, di sisi yang lain dengan payungnya Masyumi. Namun harap di catat, pemversusan ini bukan bermaksud untuk menghadap-hadapkan keduanya sebagai ‘musuh’ yang meniscayakan kekerasan diantara keduanya. Tidak, sama sekali tidak.
Namun, memang semata hanya ingin menunjukkan bahwa keduanya memang berbeda. Apalagi secara ideologis. Secara gamblang penulis bisa tunjukkan dalam sejarah kelahiran PMII saat, yang sejatinya tidak bisa dilepaskan dari eksistensi HMI.
Dalam pandangan sejarah, PMII lahir karena beberapa factor—yang dalam hal ini, subjektif: pertama, carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959. Saat itu, banyak organisasi kemahasiswaan yang berdiri di bawah payung induknya. SEMMI (dengan PSII), KMI (dengan PERTI), HMI (lebih dekat ke MASYUMI), IMM (dengan Muhammadiyah), dan HIMMAH (dengan Al-Washliyah).
Kedua, tidak menentunya sistem perundang-undangan yang ada saat itu. Ketiga, pisahnya NU dari Masyumi. Keempat, tidak enjoynya lagi mahasiswa NU yang tergabung di HMI karena tidak terakomodasinya dan terpinggirkannya mahasiswa NU. Kelima, Kedekatan HMI dengan salah satu parpol yang ada (Masyumi) yang nota bene HMI adalah underbouw-nya.
Dari perspektif historis di atas, kita bisa melihat betapa PMII, dan terusannya ke atas (baca: NU) jelas-jelas berbeda secara ideologis, bahkan di ranah gerakan politik. Nah, jika kemudian muncul lontaran Gus Mus, bahwa dia (NU) Iri pada HMI, tentu ini menjadi menarik, bukan?
Tentu juga, pada saat yang sama kita ingin menikmati efek dari lontaran Gus Mus yang menimbulkan percikan ide penuh cita rasa. Mari kita coba kuliti tafsir apa yang ada di balik pernyataan Gus Mus dengan ‘Iri pada HMI’.
Mengapa Gus Mus Iri?
Paling tidak ada beberapa ‘tafsir’ yang bisa dihadirkan dari ‘teks’ lontaran Gus Mus ini. Tafsir yang pertama, bisa jadi Gus Mus mengatakan itu sebagai makna yang sejatinya. Bahwa beliau benar-benar memuji gerakan sosial dan politik yang dikembangkan oleh organisasi HMI.
Untuk soal ini, publik telah mengamininya. Lihatlah kiprah mereka di sayap politik. Meski para tokohnya berbeda “rumah politik” namun seperti yang dikatakan Gus Mus, mereka tetap memegang identitas asalnya. Orang-orang seperti Akbar Tandjung, Anas Urbaningrum, Fery Mursyidan Baldan, dll adalah contohnya. Hingga suatu waktu, Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat pernah menuturkan bahwa “Kita harus mengapresiasi HMI. Lembaga ini sudah melahirkan cukup banyak pemimpin bangsa. Bahkan di seluruh lembaga-lembaga politik ada alumni HMI. Termasuk di level pengambil kebijakan, mulai dari menteri hingga lurah.
Ini artinya, lontaran Gus Mus memang benar adanya, dan menemukan konteksnya.
Tafsir kedua, lontaran mertua Ulil Abshar Abdalla ini bisa jadi menjadi makna kias. Makna itu, mengarah ke jantung NU. Bagaimanapun, beliau adalah tokoh NU. Tapi kenapa lontarannya justru memuji organisasi lain, bukan organisasi sendiri, bukan NU, PMII, IPNU dan lainnya? Apakah Gus Mus tengah memainkan peran dengan mengatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman sendiri? Bisa ya, bisa tidak.
Tradisi dan Kemajuan
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hanyalah Gus Mus (dan Tuhan-lah) yang tahu. Namun setidaknya, penulis ingin mengarahkan bahwa lontaran itu (semoga) menjadi kritik yang bisa membangun warga NU sendiri yang selama ini terstigmakan sebagai jumud, oportunis, puritan, tradisional dan anti modern.
Bahwa kemudian Gus Mus mencerminkan diri—dan (mungkin) secara kelembagaan, NU misalnya—kepada solidnya HMI di kancah politik dan sosial kemasyarakat serta birokrasi pemerintah, itu boleh saja. Bahkan kita di tuntut untuk selalu ‘iri’ (pada yang lebih baik) agar kita terpacu untuk mengakselerasikan segenap daya dan upaya menuju kemajuan dan keberkembangan, seperti apa yang kita iri (dan bayangkan) itu.
Ini tentu berimplikasi agar kita sementara menolak teori Max Weber yang memunculkan tesis tentang “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme” (Die Protestantische Ethic Und Der Geits Des Kapitalismus, 1930). Tesis weber memercikkan pesan bahwa protestanisme, etos kerja dan budayanya (badi dia saat itu) telah mampu membangkitkan semangat kapitalistik (modernisasi, kemajuan, dan segala macamnya) sebuah bangsa. Atau dalam makna yang kita kaitkan, bahwa dengan logika Weber ini segala macam identitas NU yang menempel seperti tradisi (turats), kejumudan dan terusannya, akan menjadi hambatan untuk menuju pada kemajuan, keberkembangan dan seterusnya.
Coba kita balikkan logika tersebut. Justru dengan tradisi negeri seperti Jepang telah memanfaatkan modal identitas tradisionalnya menjadi negara yang diperhitungkan di kancah dunia. Mereka nyatanya mampu masuk era persaingan global yang penuh nuansa modernisasi-kapitalistik. Maka, sangat masuk akal kalau Sosiolog Amerika Robert N Bellah pun menyatakan bahwa bukan (budaya) protestanisme saja yang mampu membangkitkan semangat kapitalistik suatu bangsa. Pendapat Bellah ini sekaligus menjadi antitesis Weber di atas.
Masyarakat Jepang membuktikan, tradisi justru bisa dijadikan landasan kokoh bagi pengembangan modernisasi, bahkan kapitalisasi. Kenyataan bahwa masyarakat Negeri Sakura ini mampu menjadi kekuatan industri yang maju, menggambarkan kehebatan kearifan-kearifan lokal (local wisdom) mengatasi arus globalisasi yang sangat Barat (western). Kearifan lokal itu tidak terkalahkan oleh penetrasi nilai-nilai Barat, sebaliknya menjadi kekuatan transformatif yang dahsyat.
Inilah gambaran yang diharapkan bisa ditiru oleh NU sebagai organisasi yang lekat dengan nilai-nilai tradisi, cap terbelakang, puritan dan segala macamnya. Dan pengamat NU Greg Fealy telah meng-iya-kan dalam bukunya “Ijtihad Politik Ulama”. Bahwa dengan tumpuan pada tradisi dan pilihan “jalan damai”, NU hendak menganjurkan keluwesan, pengutamaan azas manfaat dan menghindari hal-hal yang ekstrem, dan tentunya mewujudkan mimpi Robert N Bellah di atas.
Bukankah kesadaran ini yang dimaksudkan Gus Mus ketika melontarkan “Iri pada HMI”? Semoga. Wallahua’lam bi showab.
***
Jakarta, 16 Desember 2007
berikut ini beritanya:
Gus Mus Iri Pada HMI
PATI – Kekurangdekatan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang berpolitik praktis dan ormas itu jadi sorotan para kiai. Para kiai NU dari berbagai pesantren yang tergabung dalam Majma’ al Buhuts al Nahdliyah pun menginginkan mereka tak lupa asal-usul.
Forum di Pondok Raudlah Al Thahiriyah, Desa Kajen, Margoyoso, Pati, kemarin, itu merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan kiai pesantren di berbagai tempat. KH Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Dimyati Rois, KH Mahfud Ridwan MA, KH Dian Nafi’, dan KH A Muadz Thohir bertindak sebagai pengundang.
Hadir Rais Aam PBNU KH MA Sahal Mahfudh dan fungsionaris PBNU Drs H Ahmad Bagjda. Warga NU yang saat ini aktif dalam partai politik pun diundang untuk berdialog dengan tema “Mencari Format (Wadah) Pengelolaan Naluri Politik Warga NU”.
KH Sahal mengaku prihatin karena warga NU yang saat ini duduk di DPR tak kenal NU lagi. “Bagaimana saya menyampaikan aspirasi jika kenal saja tidak?”
Karena itu pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Margoyoso, Pati, itu mendukung upaya mencari format yang baik untuk berkiprah dalam politik praktis. Namun, kata dia, perlu arah gerakan yang sejalan antara politik praktis dan politik nonpraktis.
Dia menyatakan NU memang tak bisa dilepaskan dari politik. Namun pemahaman sebagian besar warga NU tentang politik saat ini adalah sebagai ajang mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan. Padahal, ada politik nonpraktis yang dipraktikkan
kiai NU terdahulu untuk memperjuangkan sesuatu yang sangat agamais.
“Dalam politik kita selama ini tak pernah mengevaluasi diri masing-masing. Kalau tidak puas pada salah satu partai, lalu membuat partai baru,” ujarnya.
Gus Mus menyatakan iri pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bisa menjaga identitas, meski berbeda partai politik. “Adapun orang NU yang masuk partai politik, mencopot kacamata NU-nya. Menurut pendapat saya, itu merugikan NU. Padahal, kita punya agenda berbangsa dan bernegara.”
Karena itu, dia berharap NU bisa menjadi rumah bagi warganya. Jadi setiap kondisi dan permasalahan yang muncul dalam progam NU bisa dibicarakan dan dicarikan pemecahan. Ahmad Bagdja yang mewakili Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat untuk mengupayakan hal itu perlu perubahan cara berpikir. “Kalau pada awal reformasi Gus Mus sering menyebut istilah islah yang diartikan perbaikan, itulah yang harus dilakukan. Jadi harus diawali dari perubahan pribadi yang mengarah ke perubahan kehidupan yang terkendali,” ucapnya.
Sementara itu, dialog lanjutan yang dipandu guru besar Unair Prof DR Kacung Marijan berhasil merumuskan beberapa rancangan rekomendasi yang akan digodok lebih lanjut. Misalnya, PBNU diminta memberikan panduan konkret bagi warganya yang berpolitik praktis berupa rumusan kepentingan dalam bidang agama, pendidikan, budaya, kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu perlu perumusan kode perilaku bagi politikus NU untuk meneguhkan jati diri sebagai kader dalam melaksanakan hak politik warga NU. Hal itu disesuaikan dengan keputusan Muktamar Ke-28 NU tahun 1989 di Yogyakarta. (H49-53)